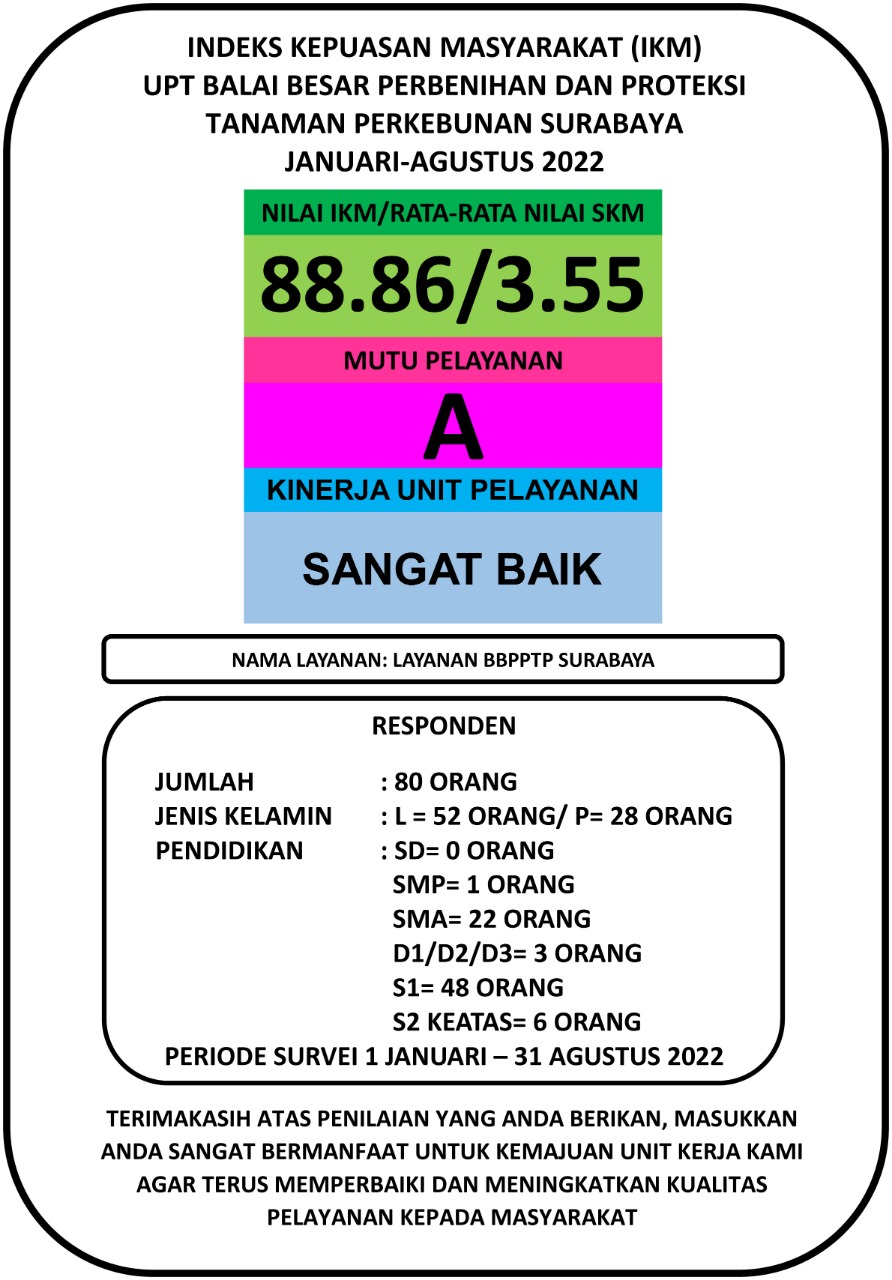MENGENAL KEMUNDURAN BENIH DAN PENYEBABNYA
Diposting Jumat, 30 September 2022 07:09 amOleh :
Dwithree Desfajerin D., SP., MP.
PBT BBPPTP Surabaya
Benih merupakan sarana produksi utama dalam budidaya tanaman karena dalam benih terdapat kandungan materi genetik dan kandungan kiwiawi yang merupakan komponen kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kandungan materi genetik ini akan mewarisi sifat-sifat genetik yang dimiliki tetuanya baik itu sifat unggul maupun sifat negatifnya. Sedangkan kandungan kimiawi benih akan berpengaruh pada proses awal pertumbuhan tanaman. Apabila kandungan kimiawi benih tidak maksimal dikarenakan faktor-faktor yang ada pada proses pembentukan benih tidak mendukung, niscaya benih tersebut akan mengalami kesulitan dalam awal pertumbuhannya.
Kemunduran benih merupakan suatu proses yang merugikan yang dialami oleh setiap jenis benih yang dapat terjadi segera setelah benih masak dan terus berlangsung sampai penyimpanan. Copeland dan McDonald (2001) mengemukakan bahwa kemunduran benih adalah proses mundurnya mutu fisiologis benih secara berangsur-angsur dan kumulatif serta tidak dapat balik (irreversible) akibat perubahan fisiologis dan biokimia. Perubahan yang menurun sehingga meningkatkan paparan benih terhadap tantangan eksternal dan menurunkan kemampuan benih untuk bertahan hidup juga merupakan kemunduran benih, dimana hal tersebut akan mengurangi kelangsungan hidup dan akhirnya menyebabkan kematian benih (Jyoti dan Malik, 2013).
Proses alami dalam kemunduran benih melibatkan sitologi, perubahan fisiologis, biokimia dan fisik dalam benih. Urutan kemunduran benih dimulai dengan rantai peristiwa biokimia terutama kerusakan membran dan penurunan reaksi biosintetik yang menghasilkan kehilangan beberapa tanda kinerja benih, dimulai dengan penurunan daya berkecambah, penurunan perkecambahan di lapang, peningkatan kecambah abnormal dan diakhiri dengan kematian benih (Jyoti dan Malik, 2013). Lebih lanjut Copeland dan McDonald (2001) menjelaskan gejala kemunduran pada benih dapat dicirikan dengan terjadinya perubahan morfologi (perubahan warna kulit benih menjadi lebih gelap dan terjadinya nekrosis kotiledon), perubahan ultrastruktural (penggabungan lemak dan plasmalemma), ketidakmampuan benih untuk menahan metabolit seluler yang bocor ketika terjadi imbibisi, kehilangan aktivitas enzim, dan respirasi yang menurun.
Kemunduran benih dapat terjadi selama penanaman, pemanenan dan penyimpanan. Selama penanaman, kemunduran benih akan dimulai saat benih telah masak fisiologis sampai benih tersebut dipanen. Kondisi lingkungan sebelum panen yang merugikan akan mengakibatkan benih yang telah masak fisiologis mengalami kerusakan. Saat panen sampai setelah panen, benih umumnya mengalami kerusakan fisik akibat dari cara panen, prosessing, dan transportasi yang kurang tepat (Jyoti dan Malik, 2013).
Selama penyimpanan, sejumlah perubahan fisiologis dan fisikokimia terjadi, disebut penuaan benih. Penuaan benih secara umum ditandai oleh penurunan vigor, viabilitas, laju dan kapasitas perkecambahan, peningkatan kebocoran zat terlarut dan kerentanan terhadap stress dan mengurangi toleransi untuk penyimpanan dalam kondisi sub-optimum (Nik et al., 2011). Shaban (2013) menjelaskan bahwa pada tingkat sel, penuaan benih dikaitkan dengan berbagai perubahan termasuk hilangnya integritas membran, metabolisme energi berkurang, penurunan RNA dan sintesis protein, dan degradasi DNA. Penuaan benih juga menyebabkan penyimpangan kromosom yang tergolong sebagai efek mutagenik yaitu terdiri fragmentasi, jembatan, fusi, pembentukan cincin kromosom dan variasi ukuran inti (Jyoti dan Malik, 2013).
Kehilangan integritas membran sel adalah salah satu penyebab utama hilangnya viabilitas. Gangguan permeabilitas membran mengakibatkan peningkatan pencucian konstituen benih. Perubahan sistem membran, seperti tonoplast, plasmalemma dan retikulum endoplasma mengakibatkan berkurangnya fungsi sel normal dan produksi energi. Sehingga penurunan perkecambahan dan vigor benih berhubungan dengan tingginya tingkat kebocoran elektrolit (Jyoti dan Malik, 2013). Rathinavel dan Dharmalingan (2001) menjelaskan bahwa peningkatan permeabilitas sel dari benih kapas saat kemunduran benih memungkinkan komponen sel berdifusi keluar dalam jumlah besar saat benih ditempatkan dalam air.
Enzim memiliki peran penting dalam kemunduran benih dan perubahan aktivitas enzim dapat menjadi indikasi penurunan kualitas (Copeland dan McDonald, 2001). Jyoti dan Malik (2013) menjelaskan bahwa semua aktivitas enzim berkorelasi positif dengan perkecambahan jika aktivitas enzim menurun seperti berkurangnya aktivitas lipase, ribonuklease, asam fosfatase, protease, diastase, katalase, peroksidase, α dan β amilase, DNase dan dehidrogenase maka perkecambahan juga menurun. Penurunan aktivitas enzim dalam benih akan menurunkan kapasitas pernafasan, yang selanjutnya akan menurunkan energi (ATP) dan pasokan asimilat untuk benih berkecambah. Oleh karena itu, beberapa perubahan dalam struktur makromolekul enzim dapat berkontribusi untuk menurunkan efisiensi perkecambahan (Shaban, 2013).
Reactive oxygen spesies (ROS) dan hidrogen peroksida yang dihasilkan dari beberapa reaksi metabolisme dan bisa dihancurkan oleh aktivitas enzim pembersih seperti katalase (CAT) dan peroksida (POD). Namun aktivitas peroksida menurun dengan adanya penuaan benih akibatnya benih menjadi lebih sensitif terhadap efek oksigen dan radikal bebas dalam membran asam lemak tak jenuh dan menghasilkan produk-produk peroksidasi lipid seperti monaldehyde dan gabungan lipid (Jyoti dan Malik, 2013). Produksi radikal bebas, terutama yang diprakarsai oleh oksigen, berhubungan dengan peroksidasi lipid dan senyawa penting lain yang ditemukan dalam sel. Hal ini menyebabkan sejumlah kejadian yang tidak diinginkan termasuk penurunan kadar lipid. Peroksidasi lipid dimulai dengan munculnya radikal bebas (atom atau molekul dengan elektron yang tidak berpasangan) baik oleh autoksidasi atau enzimatis oleh enzim oksidatif seperti lipoxygenase yang terdapat dalam benih (Shaban, 2013).
Peroksidasi lipid dimediasi oleh radikal bebas, inaktivasi enzim atau penurunan protein, disintegrasi membran sel dan kerusakan genetik. Shaban (2013) menjelaskan bahwa proses biokimia peroksidasi lipid merupakan penyebab kemunduran selama penyimpanan benih. Peroksidasi lipid dan produk yang dihasilkan dari proses ini menyebabkan denaturisation DNA, menghalagi translasi dan transkripsi protein, dan menyebabkan oksidasi asam amino. Mekanisme kerusakan oksidatif sangat kompleks dan terjadi sebagai perubahan dua jenis asam lemak. Yang pertama, terkait dengan proses penuaan pada minggu pertama penyimpanan dan termasuk oksidasi asam lemak tak jenuh spontan, tanpa terjadi perubahan pada asam lemak jenuh. Kedua, hilangnya kemampuan benih untuk berkecambah menunjukkan oksidasi kedua asam lemak jenuh dan tak jenuh.
Aktifitas radikal bebas dalam benih tergantung pada kadar air, komponen benih (misalnya keutuhan benih, kotiledon, embrio), banyak benih, spesies dan varietas, serta perlakuan penuaan. Perubahan peroksidatif dalam komposisi asam lemak dari membran lipid berpengaruh pada viskositas, permeabilitas dan fungsi membran sel serta penurunan respirasi mitokondria selama penyimpanan. Produk akhir peroksidasi lipid adalah lipid hydroperoxid (ROOH) dari aldehida yang dibentuk, termasuk malonil-dialdehyde (MDA). Penentuan kadar MDA adalah metode konvensional yang digunakan untuk penentuan peroksidasi lipid (Shaban, 2013).
Kimia dan susunan minyak dalam benih juga mempengaruhi kerentanan benih terhadap kemunduran. Kimia benih berpengaruh pada jumlah air bebas yang tersedia untuk benih akan meningkatkan tingkat kemunduran. Benih yang memiliki lendir di sekitar kulit biji seperti Salvia pada lingkungan dengan kelembaban relatif tinggi akan mentransfer kelembaban ke benih sehingga mengakibatkan kemunduran benih lebih cepat. Pada benih berminyak, komposisi asam lemak merupakan faktor penting yang menentukan kerentanan minyak terhadap oksidasi (Shaban, 2013).
Benih dengan kandungan lipid yang banyak mempunyai umur simpan yang terbatas karena komposisi kimia spesifik. Selama penyimpanan, pada benih berminyak terjadi penurunan total jumlah kandungan minyak dan perkecambahan. Komposisi asam lemak adalah faktor yang paling penting yang menentukan kerentanan minyak terhadap oksidasi. Parameter kualitas benih seperti kandungan minyak, komposisi asam lemak dan kadar protein secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan dan waktu (Shaban, 2013).
Basra et al. (2000) menyatakan bahwa asam lemak bebas memiliki efek merusak pada membran. Mitokondria tanaman terisolasi menunjukkan pembengkakan dan mengeluarkan fosforilasi oksidatif dengan adanya asam lemak bebas. Penambahan asam lemak bebas meningkatkan fusi vesikula tanaman yang mengakibatkan peningkatan kebocoran membran. Asam lemak bebas yang merusak lipid bilayer khususnya mitokondria menyebabkan produksi energi berkurang dan radikal bebas. Hal tersebut memiliki potensi untuk merusak membran, DNA, enzim, protein dan mekanisme perbaikan sel (Jyoti dam Malik, 2013). Copeland dan McDonald (2001) juga menjelaskan bahwa akumulasi terus-menerus asam lemak bebas berakibat pada pengurangan pH seluler dan merugikan metabolisme sel normal.
DAFTAR PUSTAKA
Basra, S.M.A, K.U.Rehman and S. Iqbal. 2000. Cotton seed deterioration : assessment of some physiological and biochemical Aspects. Int. J. Agri. Biol. 2 (3): 195-198.
Copeland, L. O. and M. B. McDonald. 2001. Principles of Seed Science and Technology. Burgess Publishing Company. New York. 467 p.
Jyoti and C.P. Malik. 2013. Seed deterioration : a review. Int. J. LifeSc. Bt and Pharm. Res. 2 (3): 374-385.
Nik, S.M.M., H.G. Tilebeni, E. Zeinali, and A. Tavassoli. 2011. Effects of seed aging on heterotrophic seedling growth in Cotton. American-Eurasian J. Agri. And Environ. Sci. 10 (4): 653-657.
Rathinavel, K. and C. Dharmalingam. 2001. Efficacy of seed treatment on storabilly of cotton seeds and seedling vigour. Jounal of Tropical Agriculture. 39 (2001): 128-133.
Shaban, M. 2013. Review on physiological aspects of seed deterioration. Intl. J. Agri. Crop. Sci. 6 (11): 627-631.